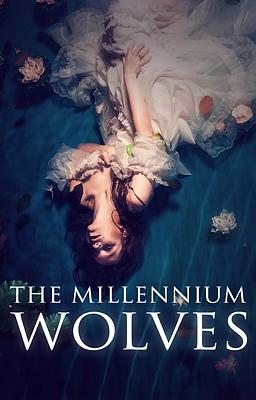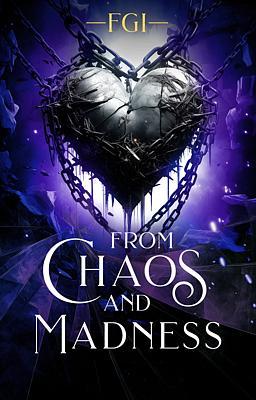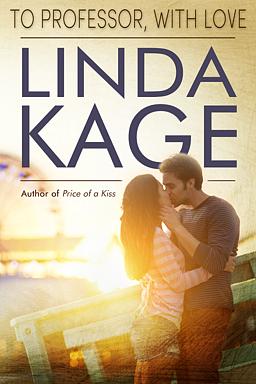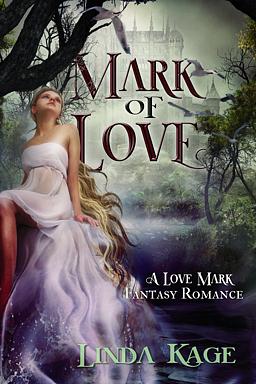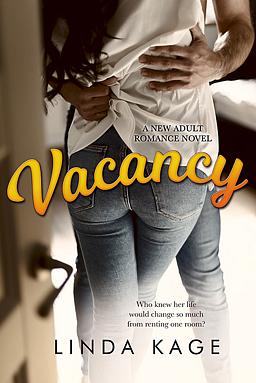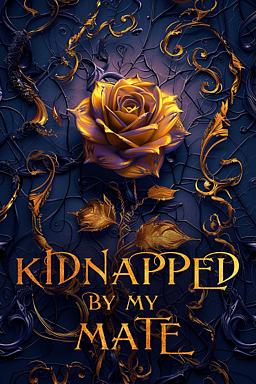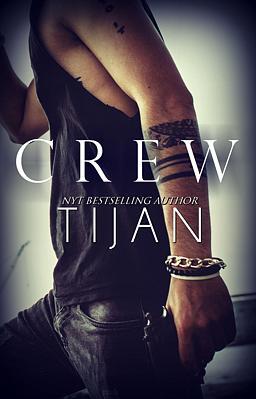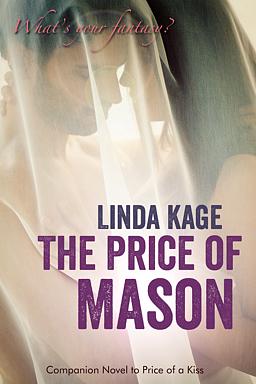Putri yang Hilang
Author
Holly Prange
Reads
🔥22,0M
Chapters
49
Everly telah hidup dalam ketakutan sepanjang hidupnya, tetapi situasi memburuk ketika ibu tirinya yang kejam menjualnya sebagai budak. Dipaksa untuk hidup di dunia monster yang kumuh dan haus akan darah perawannya, Everly merasa putus asa—sampai dia berhasil melarikan diri ke Kawanan Bulan Merah. Di sana, dia bertemu dengan Alpha Logan yang tampan, jodohnya yang ditakdirkan. Namun, tuan lamanya mencium jejaknya. Akankah kawanan barunya dapat mengalahkan mereka?
Bab 1
EVERLY
“Everly! Ayo bangun, jangan malas! Aku lapar!" Suara bibiku yang keras dan menjengkelkan terdengar dari ujung tangga.
Aku menghela napas lelah sambil membuka kembali selimut tipis yang gatal sebelum bergegas untuk berpakaian.
Aku segera menarik gaun cokelat pudar yang terlipat di kursi di sudut.
Gaun ini salah satu dari tiga pakaian milikku, semuanya buatan Bibi Lutessa.
Dia mendapat dana tunjangan bulanan dari rekening yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Uang itu seharusnya digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhanku.
Namun, dia mengeklaim uang itu hanya cukup untuk membeli makanan dan membayar tagihan agar air dan listrik kami tetap menyala dan membayar sewa rumah kami.
Namun, aku tahu dia berbohong. Setiap kali dia menerima uang itu, dia pulang dengan satu tas pakaian baru dan perhiasan untuk dirinya sendiri.
Aku melihat diriku di cermin retak yang disandarkan ke dinding dan menghela napas sebelum mengikat rambut hitam panjangku menjadi kucir kuda.
Aku bergegas menuruni tangga dan ke dapur, dan mendapati bibiku duduk di meja, sedang main ponselnya.
Aku tidak yakin dia sedang apa, meskipun aku yakin itu tidak penting.
Dari apa yang aku lihat, dia sedang memainkan salah satu akun media sosialnya.
"Sudah waktunya makan, dasar kau tidak berguna, anak nakal tidak tahu terima kasih," komentarnya saat dia melihatku memasuki ruangan.
“Maafkan aku, Bibi Tessa. Aku ketiduran,” gumamku sambil menunduk. Aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak memicu sisi buruknya keluar, atau mungkin aku harus bilang, sisi yang lebih buruk.
“Aku tidak ingin dengar alasan, dasar pelacur kecil! Buatkan aku sarapan saja agar aku bisa mulai bekerja! Salah satu dari kita perlu mencari nafkah!”
"Ya, Bibi. Maaf, Bibi,” jawabku cepat sambil mulai mengeluarkan bahan-bahan dari lemari es.
Aku membawa semuanya ke kompor dan mulai membuatkan telur dadar ham dan keju dengan tomat dan bayam.
Perutku keroncongan dan liurku mengalir saat melihat makanan di atas kompor. Aku berharap bisa ikut makan.
Bibiku hanya mengizinkan aku makan sisa dari piringnya, yang biasanya tidak banyak. Aku mengambil makanan diam-diam sebisaku, tetapi aku harus berhati-hati.
Dia pernah memergokiku makan sisa makanannya di lemari es, dan aku dipukuli. Aku sakit dan hampir tidak bisa bergerak selama berhari-hari setelah itu.
Aku benci hidupku sekarang. Dulu hidupku indah. Orang tuaku luar biasa dan penuh kasih.
Mereka selalu membuatku tertawa dan mengatakan betapa mereka mencintaiku. Mereka akan menghiburku dan memelukku setiap kali aku terluka atau sedih.
Kami begitu dekat. Kemudian, enam tahun yang lalu, kecelakaan mobil menewaskan kedua orang tuaku.
Malam itu, aku seharusnya bersama mereka, tetapi malah main dengan seorang teman. Sekarang, setiap hari aku menyesal tidak bersama mereka saat itu. Aku rindu mereka.
Aku merindukan kehidupanku yang dulu. Aku merindukan rumahku yang besar dan indah dengan taman besar di belakang tempatku bermain. Saat itu aku punya teman, orang tua; dulu aku bahagia.
"Berhentilah melamun, dasar sapi gemuk!" Bibi Tessa berteriak, menyadarkanku dari lamunan.
Aku memindahkan telur dadar ke piring dan membawa ke hadapannya sebelum menuangkan secangkir kopi untuknya dengan krim pilihannya dan sedikit susu.
Aku mulai berjalan pergi untuk memulai sisa tugas hari itu sebelum dia menghentikanku.
“Aku kedatangan tamu malam ini. Rumah harus bersih. Dan sementara dia di sini, sebaiknya kau tidak meninggalkan kamarmu. Jangan bersuara,” perintahnya, jarinya menunjuk wajahku, mengancam..
Aku segera mengangguk sebelum bergegas pergi.
Bibi sering kedatangan tamu pria yang berbeda yang mengajaknya keluar; sering kali mereka pulang ke rumah dan dan menuju ke kamar tidurnya.
Sementara itu, aku berpura-pura tidak ada di kamarku, yang sebenarnya ruang loteng kecil di atas ruang tamu.
Sisa hari dihabiskan untuk membersihkan debu, menyapu, mengepel, mencuci piring dan mencuci, dan membersihkan kamar mandi dan yang lainnya.
Aku tidak perlu memberi Bibi alasan lain untuk memukulku. Aku baru saja selesai ketika mendengar bel pintu.
Setelah tersentak kaget, aku melihat ke pintu depan, berdebat dalam hati apakah harus membukanya atau tidak.
Dia biasanya tidak ingin ‘tamu’-nya tahu aku di sini, tapi aku yakin dia akan marah kepadaku kalau tamunya pergi karena aku tidak membiarkan mereka masuk.
Aku berdiri di sana sejenak sebelum menghela napas dan berjalan menuju pintu.
Aku membukanya dan melihat seorang pria berdiri di depanku dengan janggut hitam dan kumis.
Dia memiliki garis rambut yang surut, dan hanya beberapa inci lebih tinggi dariku.
Mata cokelatnya dengan cepat menyipit ke arahku saat menyapu tubuhku, membuatku merasa mual.
Sudut mulutnya yang tipis membentuk seringai, dan tubuhku langsung menegang.
Aku tidak merasa nyaman dengan cara orang ini melihatku, dan sekarang aku menyesal membuka pintu.
Aku menutupnya sedikit sehingga siap membantingnya di wajahnya jika perlu.
Aku berusaha berdiri setegak mungkin dan mengumpulkan kepercayaan diri semampuku, lalu bertanya, "Ada yang bisa kubantu?"
“Aku ingin bertemu Lutessa. Aku tidak tahu kalau dia punya pembantu…,” katanya saat dia mendekat, dan aku melawan keinginan untuk mundur.
"Dia belum pulang," jawabku sebelum berhenti, tidak yakin apa lagi yang harus kukatakan. Haruskah aku memintanya untuk meninggalkan pesan? Atau untuk kembali nanti?
Haruskah aku menawarkan dia minuman? Haruskah aku membiarkannya menunggu di ruang tamu?
Aku tidak suka ide berduaan dengannya, tapi aku tidak yakin bagaimana reaksi Lutessa jika aku menyuruhnya pergi.
"Tidak apa-apa. Aku akan menunggu,” kata pria itu sambil maju masuk ke ruang depan, menyebabkan aku tersandung ke belakang.
Dia menangkap pinggangku dan menarikku mendekat, membuatku merinding mencium bau rokok basi.
Dia bertahan lebih lama dari seharusnya, dan aku dengan cepat menggeliat keluar dari genggamannya dan menjauh.
“O—Oke, k—kau bisa menunggu di si—di sini, kalau begitu,” aku tergagap saat sarafku mulai menguasai diriku.
Dia menyeringai, sepertinya menikmati kenyataan kalau dia membuatku gugup.
Dia melenggang ke arahku saat aku terus mundur sampai menabrak dinding.
Tangannya naik di kedua sisiku, mengurungku saat dia mencondongkan tubuh ke arahku dan berbicara dengan lembut di dekat telingaku.
“Aku bisa memikirkan beberapa cara untuk menghabiskan waktu…,” dia memulai saat tangannya mulai bergerak naik ke pahaku dan di bawah ujung gaunku.
Aku meraih pergelangan tangannya, menghentikan pergerakannya, dan matanya bertemu dengan mataku.
"Berhenti," jawabku memaksa.
"Berhentilah menggoda seperti itu," katanya sebelum menarik tangannya dari cengkeraman eratku.
“Aku—aku tidak menggoda. Aku hanya tidak t—tertarik,” aku tergagap sebelum mengambil napas dalam-dalam untuk mengembalikan ketenanganku.
"Lutessa akan segera pulang, dan kau bisa menunggu di sofa," aku memberitahunya dengan tegas sebelum berbalik untuk pergi.
Dia meraih pergelangan tanganku dan menarikku ke arahnya, dan secara naluriah aku menyerangnya dengan tanganku yang bebas.
Pukulan keras bergema di seluruh rumah kecil itu, diikuti oleh keheningan yang menegangkan.
Mataku melebar saat wajahnya menjadi serius dan dia berbalik menatapku. "Kau jalang kecil!" Dia mulai maju ke arahku lagi, dan aku berbalik untuk lari.
Kepalaku ditarik ke belakang saat dia meraih segenggam rambutku. Aku menjerit sebelum dia membantingku ke dinding.
Bintik-bintik gelap menari-nari dalam pandanganku saat aku berlutut.
Dengan membabi buta, aku mengulurkan tanganku, mencoba memaksakan diri berdiri, tetapi tinjunya mengenai wajahku dan aku jatuh ke belakang.
Aku mengerang sambil menggeliat di lantai karena rasa sakit. "Tolong!" Aku memohon. "Berhenti!"
Dia tidak mendengarkan sambil membalik tubuhku dan memanjat di atasku sehingga dia mengangkangi pinggulku.
“Oh, diamlah, pelacur kecil. Beri apa yang aku mau,” dia menuntut sebelum meraih leher gaunku dan merobek bagian depan, memperlihatkan bra polos yang aku kenakan di bawahnya.
Tanganku terulur ke depan saat aku mencoba mendorongnya menjauh.
Dia berjuang untuk meraih pergelangan tanganku, dan akhirnya aku berhasil mengambil asbak keramik berat yang ada di meja konsol.
Aku menghancurkannya di atas kepalanya dan dia jatuh dariku.
Aku segera bangkit untuk melarikan diri, tapi tangannya melesat keluar dan mencengkeram pergelangan kakiku, membuatku jatuh tertelungkup.
Saat itu, aku bisa mendengar suara pintu depan saat kenop diputar dan dibuka. Bibi Tessa masuk dan langsung membeku saat melihat kami.
"Apa yang terjadi di sini?!" dia berteriak sambil berjalan ke arah kami sementara pria itu bergegas untuk berdiri.
Saat aku berjuang untuk berdiri, bibiku menarik lenganku.
"Apa kau merayu Dean, dasar kau gelandangan tak berguna?!" dia menjerit sambil mengguncangku dengan kasar.
“T—TIDAK! Di—dia mencoba memperkosaku!”
"PEMBOHONG!" dia berteriak seraya mengguncangku lagi.
“Pria mana yang akan mengejar pelacur gemuk dan jelek sepertimu?! Kau bukan apa-apa! Dan ini saatnya kau belajar!”
Dia menarikku berdiri di depannya sebelum menampar wajahku.
Sengatannya terasa seketika begitu tanganku menutupi pipiku dan air mata memenuhi mataku.
Wajahnya sedikit tenang sebelum dia beralih ke pria cabul yang hanya berdiri di sana menyaksikan adegan itu terjadi.
"Dean, tunggu aku di mobil. Aku perlu memberi pelajaran kepada pelacur ini sebelum kita kencan. Aku akan segera menyusul.”
Dia menatapku tajam dan mengangguk sebelum berbalik untuk pergi.
Aku menyeka pipiku yang basah saat mendengar pintu ditutup, dan bibiku pergi ke lemari mantel dan kembali dengan ikat pinggang.
"Tolong, Bibi Tessa," aku memohon padanya. “Aku t—tidak berbohong! Dia me—memaksa masuk. Dia—dia memukulku…”
"Kenapa kau selalu menghancurkan hidupku?!" dia berteriak kepadaku sambil melecut ikat pinggang ke tubuhku seperti cambuk.
Aku langsung mengangkat tangan menutupi tubuh untuk melindungi diri, dan sabuk itu menggigit lengan bawahku.
Dia meraih tubuhku dan mendorongku ke lantai, dan aku jatuh terjerembab sebelum dia memukulku dengan ikat pinggang lagi.
Dia memukulku berulang kali saat aku meringkuk di lantai, dan sebisa mungkin berusaha melindungi kepala dan leherku dari serangannya.
Ketika akhirnya lelah, dia menjatuhkan sabuknya ke lantai dan bersandar padaku.
“Saat aku kembali, kekacauan ini lebih baik sudah dibersihkan! Kau dengar aku, pelacur malas?!”
Aku mulai terisak, hanya sanggup mengangguk pelan.
Dia berbalik dan meninggalkanku tergeletak di lantai dengan memar dan luka yang sekarang menutupi tubuhku.
Aku tetap di sana saat tubuhku bergetar oleh tangisan yang menyayat hati. Seluruh tubuhku licin dan lengket karena darah.
Rasanya sakit saat bergerak, tapi aku tidak ingin dipukul lagi.
Setelah berusaha bangkit susah payah, aku berhasil bangun dan membersihkan ruangan yang berantakan sebelum merangkak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh.
Akhirnya aku ambruk di tempat tidurku, kasur tua yang kotor tergeletak di lantai. Aku meringkuk seperti bola dan menarik selimut gatalku ke atas tubuhku.
Semua gerakanku lambat dan menyakitkan, dan jika bukan karena sangat lelah seperti sekarang, aku tidak yakin apakah bisa tertidur.
Untungnya, aku terlalu lelah, dan segera terlelap. Aku tidak tahu berapa lama sudah tertidur sebelum suara bibiku memenuhi ruangan.
“Bangun, Everly! Ganti bajumu! Kita harus pergi!” dia memerintah.
Mataku terbuka dan aku melihat sekeliling, bingung. Di luar masih gelap.
"Ada apa? Pergi ke mana?" Aku bertanya dengan mengantuk, masih mencoba memahami apa yang terjadi.
"Cepat dan lakukan apa yang aku katakan, dasar bocah tak berguna!" dia menjawab sebelum membanting pintu dan turun kembali.
Tubuhku terasa nyeri saat aku memaksa bangun dan memakai gaun putih kumal.
Aku memakai sepatuku dan turun ke bawah, Bibi Tessa menunggu di dekat pintu dengan mantelnya.
Kakinya mengetuk lantai dengan tidak sabar, dan dia menatapku saat aku mulai menuruni tangga dari loteng.
“Lama sekali, sih! Cepatlah! Kita tidak punya waktu semalaman!”
Dia membuka pintu depan dan menunjuk ke luar ke mobilnya yang diparkir di depan. “Bibi—”
"Diam! Ayo! Masuk!" Aku menggeleng dan masuk ke kursi penumpang lalu memakai sabuk pengaman.
Aku menyandarkan dahiku ke jendela saat bibiku datang dan duduk di kursi pengemudi.
Dinginnya kaca jendela terasa nyaman di kulitku, dan aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam.
Mobil berjalan cukup jauh, dan tak lama aku tertidur kembali.
Ketika terbangun, aku tidak tahu kami di mana, tetapi sudah tiga jam sejak kami meninggalkan rumah. Ke mana dia membawaku? Ada apa ini?
Aku mulai gugup. Aku duduk lebih tegak dan mulai melihat sekeliling, mencoba mencari tahu apa ada tanda atau tempat yang kukenali.
Tak lama, kami tiba di kota besar, dan dia melaju di jalan raya.
Kecemasanku terus tumbuh ketika terus berusaha mencari tahu kami akan pergi ke mana. Setiap kali, dia menyuruhku diam dan tidak mengajaknya bicara.
Perutku bergejolak saat melihat gedung-gedung di sekitar kami. Bangunan tampak semakin usang semakin jauh kami berjalan.
Akhirnya, kami berhenti di depan sebuah bangunan bata sederhana yang tampak seperti gudang dengan pintu hitam yang kokoh. Bibi menyeret aku ke sana dan membunyikan bel pintu.
Seorang pria besar dengan kaus hitam ketat dan celana jins menjawab dengan tangan disilangkan di dada. "Sebutkan nama dan keperluanmu," katanya dengan suara serak.
“Lutessa Andrews. Aku ada janji dengan Lord Vlad Lacroix,” katanya sambil terus mencengkeram lenganku dengan erat.
Penjaga itu mengangguk dan mundur, membiarkan kami lewat sebelum memandu kami melewati lorong yang gelap.
Bangunan ini persis gudang tua selain ada suara-suara yang terdengar dari ruangan yang tak tampak.
Musik keras menggelegar melalui dinding seolah-olah ada kelab malam di baliknya.
Saat kami terus berjalan, aku dapat mendengar erangan dan jeritan dari berbagai ruangan. Di setiap langkah, rasa takutku tumbuh. Di mana kami?
Kami dipandu masuk lewat satu set pintu ganda, dan tiba-tiba kami ada di ruangan dengan karpet tebal dan mewah berwarna merah tua dan putih serta berdinding hitam.
Begitu kami mencapai pintu di ujung lorong, pria itu mengetuknya, dan sebuah suara dari dalam memanggil, "Masuk."
Penjaga membuka pintu dan memberi isyarat agar kami masuk sebelum menutupnya.
Seorang pria sedang duduk di kursi bersandaran tinggi dekat meja mahoni besar.
Kulitnya pucat pasi dan rambut hitamnya disisir rapi ke belakang. Dia menarik dengan tubuhnya yang tinggi ramping dan mata abu-abunya, tapi dia juga sangat…menakutkan.
Sudut mulutnya melengkung ke atas menjadi seringai jahat saat kami masuk, dan dia berdiri dari mejanya dan mendekati kami.
Bibiku mendorongku ke depan, dan pria itu mulai berdiri memutariku seraya matanya menelusuri setiap inci tubuhku.
"Jadi, ini gadis itu?" dia bertanya dengan lembut, dan aku bertanya-tanya apa itu pertanyaan retoris.
"Ya. Ini yang aku ceritakan,” jawabnya.
Dia mengangguk saat dia mendekatiku lagi.
"Bagus. Dia akan cocok.” Dia berbalik dan berjalan menuju mejanya lalu mengambil tas cokelat kecil, membawanya, dan menyerahkan tas itu ke bibiku.
“Dan pembayaranmu. Seperti yang kita diskusikan.”
“Terima kasih, Pak,” jawab Bibi Tessa.
Aku menoleh kepadanya dengan bingung. “Pembayaran untuk apa?”
“Dia akan memberitahumu. Kau bukan masalahku lagi.” Setelah itu, bibiku berbalik dan berjalan menjauh dariku, meninggalkanku sendirian di ruangan ini bersama pria asing itu.
Aku menatapnya, menunggu penjelasan.
"Belum jelas juga, sayangku?" dia bertanya dengan nada mengejek. Alisku berkerut sambil berusaha mencerna semua ini, tapi aku tidak yakin.
Jika aku tidak mengenal bibiku dengan baik, menurutku sepertinya bibiku baru saja menjualku kepada pria ini. Namun, itu tidak mungkin benar. Bisakah begitu?
Pria itu tersenyum. “Bagus sekali, anak kecil. Kamu benar.” Mataku melebar saat perhatianku kembali ke pria itu. Aku tidak mengatakan itu dengan suara.
Apa dia baru saja membaca pikiranku? "Benar lagi," katanya dengan senyum jahat.
“Na—namun, b—bagaimana? Mengapa? Ini ilegal! Ini—” Aku tergagap, mencoba memahami segalanya.
"Hukum manusia bukan urusanku," komentarnya saat senyum jahatnya menyebar di wajahnya, menunjukkan dua taringnya yang tajam.
Matanya berubah menjadi merah padam yang terang, dan aku megap-megap karena syok sebelum semuanya menjadi hitam.